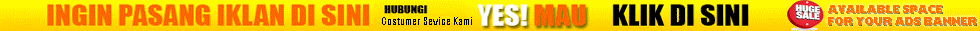Memaknai “Kiamat” 2012
BEBERAPA tahun lalu, pernah diprediksi bahwa tahun 2012 adalah
tahun terjadinya kiamat. Dunia dihebohkan dengan isu itu dan semua
perhatian sontak tertuju padanya. Sebagian mengamininya lantas mawas
diri dan sebagian yang lain menganggapnya sebagai berita bohong dan
menyesatkan dengan sikap dan respon yang beragam pula.
Namun
demikian, terlepas benar-tidaknya berita itu, kita tentu boleh saja
memandangnya sebagai hal yang positif, baik sebagai sebuah peringatan,
ujian, atau syok terapi yang dapat membangunkan kita dari kelalaian
ekologis, ketimbang mengabaikannya tanpa memerhatikan secara serius
kondisi bumi hari ini.
“2012” dan “kiamat” dapat dimaknai sebagai
sebuah pesan bahwa sangat mungkin di tahun tersebut akan terjadi
beragam bencana ekologis yang mengancam kehidupan makhluk.
Lewat
pesan tersebut, kita diharapkan semakin sadar untuk bersikap lebih
santun, bijak, dan benar dalam semua hal, terpanggil untuk menciptakan
ketentraman dan keharmonisan di muka bumi, dan merubah cara pandang yang
selama ini keliru, cenderung egois, serta rakus terhadap alam atau
lingkungan, ketimbang bersikap acuh-tak acuh, menganggapnya tidak
penting, dan mengabaikan kondisi ekologi bumi yang sangat rapuh dan
terancam. Poin penting dari isu itu bahwa kiamat boleh saja terjadi,
tetapi sikap, perbuatan, dan kerja nyata menciptakan keharmonisan di
bumi adalah suatu keniscayaan abadi yang dapat menyelamatkan manusia
seluruhnya.
Pesan “kiamat” sebagaimana yang diisukan itu bukanlah
hal baru dalam ranah ekologi. Pada tahun 1960-an pesan serupa pernah
dimunculkan para ekolog modern semisal Rachel Carson, dalam karyanya The
Silent Spring (1962), Garrett Hardin, The Tragedy of the Commons
(1968), dan dipertegas oleh Bill McKibben yang dengan lantang
meneriakkan The End of Nature (1989), atau apa yang disebut “kiamat”.
Bahkan,
berdasarkan data dari dua penelitian penting dalam A Blueprint for
Survival (1972) dan The Limits to Growth (1972), disimpulkan bahwa batas
pertumbuhan di planet ini hanya berlangsung dalam kurun waktu 100 tahun
mendatang. Kesimpulan tersebut menjadi isyarat bahwa kiamat ekologis
bakal terjadi. Namun satu catatan penting, hal itu tidak akan terjadi
apabila ekosistem bumi ini dipelihara secara lestari.
Tanpa
penelitian semacam itu pun kita sudah mengetahui bagaimana kondisi bumi
hari ini, apalagi jika dikonfirmasi langsung ke beberapa penelitian
mutakhir yang semakin membenarkan prediksi kiamat ekologis yang
dimaksud. Fakta tak terbantahkan bahwa banjir, tanah longsor, cuaca
ekstrim, badai angin, dan gempa bumi telah merenggut jutaan nyawa
manusia dan kerugian materil yang tiada terhingga. Fakta tersebut
membuktikan bahwa manusia telah lalai secara ekologis, atau apa yang
disebut oleh Mujiono Abdillah dalam Teologi Lingkungan Hidup sebagai
“kafir ekologis”.
Back to Nature!
Perubahan paradigma
merupakan hal mendesak yang harus segera dilakukan oleh semua kalangan.
Sebab, kesalahan mendasar pemicu munculnya “kiamat ekologis” adalah
dimotori oleh kesalahpahaman kita dalam memandang diri sendiri, alam
semesta (lingkungan hidup), bahkan Tuhan.
Selama ini, kita telah
jauh menyimpang dari hukum Tuhan yang semestinya. Alam yang
diperuntukkan untuk menopang kehidupan kita, dipandang sebagai objek
rendahan yang dapat dieksploitasi sekehendakya. Alam yang telah
mengajarkan manusia bagaimana menjalani hidup dengan bersahaja,
bijaksana, dan respek terhadap sesama, kita perlakukan secara kasar,
arogan, dan egois.
Padahal bagi manusia, alam sejatinya adalah media
pembelajaran, sumber pengetahuan dan kebijaksanaan yang oleh orang bijak
dilukiskannya dengan ungkapan,
“Untuk belajar bagaimana menjadi
manusia seutuhnya”. Tanpanya mustahil kita mampu mengaktual menjadi
manusia seutuhnya dan karenanya pula kita dapat mengerti arti kehidupan
dan hidup dengan keutamaan. Karena itulah, alam tidak boleh
dieksploitasi, dirusak, dikuras, dan direndahkan martabatnya. Sebab,
sebagaimana diyakini oleh orang bijak bahwa alam adalah manusia besar
(makrokosmos) dan manusia adalah alam kecil (mikrokosmos).
Manusia
adalah miniatur terkecil dari alam yang sangat besar dan padanya
terefleksi secara penuh keseluruhan yang ada pada alam. Karena itu,
merusak alam sama halnya dengan merusak manusia itu senidiri dan dapat
memantik murka Tuhan. Selaras dengan maksud tersebut, sebuah ungkapan
menyatakan bahwa: “Tujuan orang bijak adalah berharmoni dengan alam,
karena melalui harmoni ini, lahirlah harmoni dengan manusia dan harmoni
ini sendiri merupakan cerminan dari berharmoni dengan langit”.
Kalau
demikian adanya, model sikap, perilaku, dan pandangan yang merendahkan
alam (lingkungan hidup) adalah perkara yang menyimpang dari nature kita
sendiri. Karenanya, dalam kitab suci agama disebut bahwa merusak alam
adalah sebuah dosa yang dilarang keras: “Janganlah kamu membuat
kerusakan di muka bumi..” (QS. al-A’raf: 85).
Semoga kita
menyadari peran kita untuk menciptakan keharmonisan di bumi dan berharap
agar kiamat ekologis tadak pernah menerpa bumi tercinta ini.